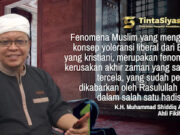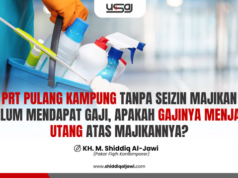Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi | Pakar Fiqih Kontemporer
Pendahuluan
Pembicaraan seputar pajak di masyarakat cukup ramai akhir-akhir ini di bulan Agustus 2025, setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa membayar pajak sama dengan membayar zakat dan wakaf. Sri Mulyani menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025), di Jakarta, yang redaksi aslinya berbunyi, ”Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak, dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan.” (www.detik.com, 13/8/2025).
Pembicaraan seputar pajak ini mungkin akan makin menghangat atau boleh jadi memanas di ruang publik, ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan mulai tahun 2026 akan memungut pajak dari pedagang eceran serta usaha makanan dan minuman. Pernyataan ini tertulis dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026 yang dirilis pada 20 Agustus 2025 yang lalu. (www.detik.com, 20/8/2025).
Bayangkan, misalnya pedagang makanan angkringan kecil-kecilan di Jogja, di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja saat ini, akan menjadi korban pajak yang semakin mengurangi pendapatan mereka. Sektor mikro ini akan dipajaki, karena dinilai rawan terjadinya aktivitas shadow economy yang berpotensi menggerus penerimaan negara, karena alasannya para pedagang kecil seperti angkringan itu menggunakan transaksi tunai yang tidak terlacak oleh sistem digital perpajakan di Indonesia. (www.detik.com, 20/8/2025).
Dalam konteks perbincangan seputar pajak inilah, perlu kiranya umat Islam memahami posisi pajak dalam Islam. Tulisan ini bertujuan menjawab sejumlah pertanyaan seputar pajak dalam Islam, yang dirumuskan dalam 5 (lima) poin pertanyaan sebagai berikut;
Pertama, apakah definisi pajak itu?
Kedua, adakah pajak dalam Islam?
Ketiga, jika pajak itu ada dalam Islam, apakah aspek-aspek persamaan dan perbedaannya dengan pajak dalam ekonomi kapitalis?
Keempat, jika pajak itu ada dalam Islam, kriteria-kriteria apa yang wajib dipenuhi agar pajak itu boleh dipungut?
Kelima, apakah pajak yang berlaku sekarang sudah sesuai dengan Syariah Islam?
Definisi Pajak
Secara etimologi, pajak merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari kata Tax dalam Bahasa Inggris. Kata Tax sendiri secara etimologi, berasal dari kata Taxare dalam Bahasa Latin, yang artinya jika sebagai verb (kata kerja) adalah memperkirakan atau menilai (to estimate or value). Sebagai kata benda (noun) kata Tax mempunyai pengertian “obligatory contribution levied by a sovereign or government” (“kontribusi wajib yang dipungut oleh penguasa atau pemerintah”). (https://www.etymonline.com/word/tax).
Secara terminologi, definisi tax (pajak) dalam literatur Bahasa Inggris adalah :
A tax is a mandatory payment or charge collected by local, state, and national governments from individuals or businesses to cover the costs of general government services, goods, and activities.
(Pajak adalah pembayaran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah, negara bagian, dan pemerintah nasional dari individu atau bisnis untuk menutupi biaya layanan, barang, dan kegiatan oleh pemerintah secara umum). (https://taxfoundation.org/taxedu/glossary/tax/).
Dalam Bahasa Arab modern, pajak disebut dengan istilah al-dharībah (اَلضَّرِيْبَةُ), atau al-dharā`ib (اَلضَّرَائِبُ), bentuk jamak (plural) dari al-dharībah. Definisinya di kalangan para ulama atau fuqoha muslim, secara umum sama maknanya dengan definisi istilah tax dalam literatur Bahasa Inggris. Definisi pajak menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani (w. 1977) adalah sebagai berikut :
اَلضَّرِيْبَةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِيْ يُؤْخَذُ مِنَ النَّاسِ لإِدَارَةِ الدَّوْلَةِ
“Pajak (al-dharībah) adalah harta yang diambil dari warga negara untuk pengelolaan berbagai urusan negara.” (Taqiyuddin An-Nabhani, Nizhām Al-Islām, hlm.86).
Definisi pajak yang ada saat ini di Indonesia, secara garis besar juga sama secara substansinya dengan definisi pajak dalam literatur ekonomi moderen, yaitu : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Lihat UU KUP [Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan] Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1).
Adakah Pajak Dalam Islam?
Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, dalam Nizhāmul Islām (hlm. 86), istilah pajak yang terdapat dalam ekonomi Barat (kapitalisme), boleh dipakai umat Islam, karena faktanya Islam juga membolehkan negara (Khuilafah) untuk mengambil harta dari warga negara untuk memenuhi berbagai keperluan negara.
Imam Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan :
وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الْكَلِمَةُ تَعْنِي اصْطِلَاحًا مَوْجُودًا مَعْنَاهُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا، مِثْلُ كَلِمَةِ ضَرِيبَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْنِي الْمَالُ الَّذِيْ يُؤْخَذُ مِنَ النَّاسِ لإِدَارَةِ الدَّوْلَةِ، وَيُوجَدُ لَدَى الْمُسْلِمِينَ مَالٌ تَأْخُذُهُ الدَّوْلَةُ لِإِدَارَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلِذَلِكَ صَحَّ أَنْ نَسْتَعْمِلَ كَلِمَةَ ضَرَائِبَ
“Adapun jika suatu kata, yaitu suatu istilah, maknanya terdapat di kalangan kaum muslimin, maka boleh menggunakan istilah itu, seperti kata “ pajak” (al-dharībah) yang berarti harta yang diambil dari rakyat untuk urusan negara, dan di kalangan kaum muslimin itu ada makna itu, yaitu harta yang diambil oleh negara untuk urusan kaum muslimin. Maka dari itu, boleh kita menggunakan istilah “pajak” (al-dharībah).” (Taqiyuddin An-Nabhani, Nizhāmul Islām, hlm. 86).
Demikian penjelasan dari segi istilah. Jadi kata “pajak” (al-dharībah), walaupun merupakan istilah dari Barat, tetapi karena maknanya secara umum juga ada di kalangan kaum muslimin, maka boleh kita kaum muslimin mempergunakan kata “pajak” (al-dharībah) itu.
Sebagai bukti bahwa makna dari istilah “pajak” (al-dharībah) juga terdapat di kalangan kaum muslimin, berikut ini kami elaborasi agak detail definisi pajak dalam empat mazhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali). Mereka memang tidak menggunakan kata al-dharībah, tetapi menggunakan berbagai istilah lain. Namun demikian, makna yang dimaksudkan hakikatnya sama dengan makna al-dharībah yang kita pahami saat ini.
Kami kutipkan berbagai istilah “pajak” tersebut dari sebuah artikel berjudul Al-Dharā`ib wa Al-Rusūm Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah, karya Dr. Ahmad bin Bilal Al-Syekh, yang dimuat di Jurnal Jāmi’ah Al-Malik ‘Abdul ‘Azīz, Fakultas Al-Adab wa Al-‘Ulūm Al-Insāniyyah, hlm. 231-276, tahun 2020, sebagai berikut :
Pertama, ulama mazhab Hanafi menyebut pajak dengan istilah al-nawā`ib (النَّوَائِبُ), yang didefinisikan sebagai berikut :
النَّوَائِبُ هِيَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ جِهَةِ السُّلْطَانِ مِنْ حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
“Pajak (al-nawā`ib) adalah pungutan yang diambil oleh pihak penguasa, baik itu yang benar, yang salah, atau yang lainnya.” (Hāsyiyah Ibnu ‘Ābidin, 2/336).
Kedua, ulama mazhab Maliki menyebut pajak dengan istilah al-wazhā`if (الْوَظَائِفُ), atau istilah al-kharāj (الخراج). Definisinya sebagai berikut :
الْوَظَائِفُ أَوْ الْخَرَاجُ هُوَ مَا قُدِّرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْخَرَاجِ أَوْ الْمَغْرَمِ.
“Pajak (al-wazhā`if/al-kharāj) adalah pungutan yang besarnya diperkirakan yang diambil dari tanah, baik pungutan itu berupa kharaj atau berupa gantirugi.” (Al-Tasūlī, Al-Bahjah fi Syarh Al-Tuhfah, 2/6).
Ketiga, ulama mazhab Syafi’i menyebut pajak dengan istilah al-tauzhif (التَّوْظِيفُ). Definisinya sebagai berikut :
التَّوْظِيفُ هُوَ مَا يُوَظِّفُهُ الْإِمَامُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ بِمَا يَرَاهُ كَافِيًا عِنْدَ خُلُوِّ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْمَالِ.
“Pajak (al-tawzhīf) adalah pungutan yang ditugaskan oleh Imam (Khalifah) kepada orang-orang kaya, dalam kadar yang mencukupi menurut pandangan Imam ketika dana di Baitul Mal kosong.” (Imam Ghazali, Syifā’ Al-Ghalīl fī Bayān al-Syabah wa Al-Mukhayyil wa Masālik Al-Ta’līl, hlm, 236).
Keempat, ulama mazhab Hambali menyebut pajak dengan istilah al-kulafu al-sulthāniyyah (الْكُلَفُ السُّلْطَانِيَّةُ). Definisinya sebagai berikut :
الْكُلَفُ السُّلْطَانِيَّةُ هِيَ مَا يَطْلُبُهُ السُّطَانُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، أَوْ مِنْ الْعَامِلِ
“Pajak (al-kulafu al-sulthaniyyah) adalah pungutan yang dituntut oleh penguasa dari pemilik harta, atau dari para pegawai.” (Imam Al-Bahūtī, Kasysyāf Al-Qinā’, 3/ 541).
Demikianlah berbagai macam definisi pajak dari empat mazhab fiqih. Kesimpulannya, mereka memang tidak menggunakan istilah al-dharībah, namun menggunakan istilah-istilah lain seperti al-nawā`ib (النَّوَائِبُ), al-wazhā`if (الْوَظَائِفُ), al-tauzhif (التَّوْظِيفُ), dan al-kulafu al-sulthaniyyah (الْكُلَفُ السُّلْطَانِيَّةُ). Namun demikian, substansi maknanya sama dengan pajak (al-dharībah) yang kita pahami saat ini, yaitu harta yang diambil oleh negara dari rakyatnya untuk berbagai urusan negara.
Ini dari segi istilah. Adapun dari segi hukum yang mengatur pajak, tentu saja ada perbedaan antara pajak dalam Islam dan pajak dalam kapitalisme yang dipungut di negeri-negeri Islam, seperti di Indonesia. Pajak dalam kapitalisme diatur dengan hukum yang sifatnya sekular (bukan dari agama), sedang pajak dalam Islam, pajak diatur dengan hukum-hukum syara’ (hukum yang bersumber dari Al-Qur`an dan As-Sunnah).
Imam Taqiyuddin An-Nabhani telah menegaskan tentang adanya atau bolehnya pajak dalam Islam, tetapi pada waktu yang sama, beliau menegaskan pajak dalam Islam itu haruslah berdasarkan hukum Islam atau berdasarkan perintah Allah SWT, bukan berdasarkan yang lain. Beliau berkata :
…يَجُوْزُ لِلْخَلِيْفَةِ أَنْ يَفْرِضَ ضرِيْبَةً عَلىَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُمْ باِلْقُوَّةِ، وَأَخْذُهَا فيِ هَذِهِ الْحَالِ لَا يَكُوْنُ بِنَاءً عَلىَ أَمْرِ السُّلْطَانِ بِهَا، بَلْ بِنَاءً عَلىَ أَمْرِ اللهِ بِهَا، فَالسُّلْطَانُ إنَّمَا يُنَفِّذُ الْأمْرَ الذَّيْ أَمَرَ اللهُ بِهَا
“…Boleh bagi Khalifah (kepala negara) mewajibkan pajak atas kaum muslimin dan boleh pula dia mengambil pajak itu dari mereka secara paksa. [Hanya saja] dia mengambil pajak dalam keadaan ini tidaklah berdasarkan perintah penguasa untuk membayar pajak, melainkan berdasarkan perintah Allah untuk membayar pajak. Penguasa hanyalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah.” (Taqiyuddin An-Nabhani, Muqaddimat Al-Dustūr, Juz II, hlm. 117).
Maka dari itu, jika terdapat suatu kewajiban syar’i (dari Allah) atas Kas Negara (Baitul Mal) dan juga atas kaum muslimin, maka kewajiban syar’i itu akan dibiayai dari harta Baitul Mal, misalnya biaya untuk kewajiban menyantuni fakir dan miskin. Pada satu sisi, menyantuni fakir dan miskin menjadi kewajiban negara, melalui zakat yang dipungut oleh negara melalui Amil Zakat sesuai firman Allah SWT :
خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Taubah : 103).
Tetapi pada saat yang sama, kewajiban menyantuni kaum fakir dan miskin, tidak hanya kewajiban negara, melainkan juga menjadi kewajiban individu muslim (rakyat), sesuai firman Allah SWT :
لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 177).
Jika dalam Baitul Mal tidak terdapat harta, atau terdapat harta namun tidak cukup untuk membiayai kewajiban syar’i itu, maka Khalifah boleh mewajibkan pajak atas kaum muslimin sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syara’. (Taqiyuddin An-Nabhani, Muqaddimat Al-Dustūr, Juz II, hlm. 117).
Jika penguasa memungut pajak untuk sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah, atau bahkan tidak ada dalilnya dari Al-Qur`an atau Al-Hadits, berarti penguasa itu telah mewajibkan pajak atas dasar kehendak penguasa itu sendiri, bukan atas dasar kehendak atau perintah Allah SWT.
Pemungutan pajak seperti ini haram hukumnya dan pelakunya akan masuk neraka kelak di Hari Kiamat, sesuai sabda Rasulullah SAW :
لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ
“Tidak akan masuk surga, siapa saja yang memungut cukai/pajak [yang tidak syar’i].” (HR Ahmad & Al-Hakim). (Taqiyuddin An-Nabhani, Muqaddimat Al-Dustur, Juz II, hlm. 117).
Persamaan & Perbedaan Pajak Dalam Kapitalisme Dan Islam
Terdapat persamaan pajak dalam kapitalisme dan Islam, yang dirangkum dalam tabel berikut ini.
| Kapitalisme | Islam | |
| 1. Bersifat Memaksa atau Tidak | Memaksa | Memaksa |
| 2. Bentuk Pajak (Natura, Uang, Jasa) | Uang | Uang |
| 3. Ada Tidaknya Imbalan Langsung | Tidak ada imbalan langsung | Tidak ada imbalan langsung |
| 4. Untuk Memenuhi Keperluan Siapa | Untuk memenuhi keperluan negara | Untuk memenuhi keperluan negara |
Tabel 1. Persamaan Pajak Dalam Kapitalisme Dan Islam
Dari tabel 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa persamaan pajak dalam Islam dan kapitalisme terdapat dalam 4 (empat) hal, yaitu :
Pertama, persamaan dalam hal bersifat memaksa (al-jabr), pajak dalam Islam dan dalam Kapitalisme sama-sama bersifat paksa. Ini dibuktikan dengan berbagai sanksi bagi warga negara yang tidak mau membayar pajak.
Kedua, persamaan dalam hal bentuk pajak, apakah dibayarkan dalam bentuk natura (misal hasil panen seperti beras, jagung, dsb) ataukah dibayarkan dalam bentuk lain. Dalam hal ini, ada kesamaan antara pajak dalam Islam dan pajak dalam Kapitalisme. Dalam kedua sistem ekonomi tersebut, pajak dibayarkan dalam bentuk uang.
Ketiga, persamaan dalam hal ada tidaknya imbalan langsung. Antara pajak dalam Islam dan Kapitalisme, sama-sama tidak menjanjikan adanya imbalan langsung setelah rakyat membayar pajak. Misalnya, setelah membayar pajak, rakyat tidak otomatis mendapat bantuan sosial, atau jalan di depan rumahnya diperbaiki, atau listriknya digratiskan, atau bensinnya digratiskan, dsb.
Keempat, persamaan dalam hal pajak itu untuk membayar kepentingan siapa. Antara pajak dalam Islam dan dalam Kapitalisme, pajak sama-sama dibayarkan oleh rakyat untuk memenuhi berbagai keperluan negara. Misalnya, digunakan untuk membayar utang negara dari pihak lain, dsb. (Syekh Mushthofa Mahmud Zaki, Al-Dharîbah fî Mîzân Al-Tasyrî’ Al-Islâmî, hlm. 12-15).
Selain persamaan, perlu diketahui juga ada perbedaan antara pajak dalam Islam dan pajak dalam Kapitalisme, yang dirangkum dalam Tabel 2, sebagai berikut :
| Kapitalisme | Islam | |
| 1. Dasar Kewajiban Pajak | Teori-teori ekonomi seputar pajak | Al-Qur`an dan al-Hadits |
| 2. Sumber Pendapatan Negara Tetap atau Tidak Tetap | Sumber pendapatan negara yang tetap | Sumber pendapatan negara yang tidak tetap |
3. Kontinuitas (Istimrariyyah) | Bersifat kontinu (terus menerus / permanen) | Bersifat tak kontinu (hanya temporal) saat kas negara tidak cukup |
| 4. Metode Untuk Mewajibkan Pajak | Dengan undang-undang | Dengan atau tanpa undang-undang |
Tabel 2. Perbedaan Pajak Dalam Kapitalisme Dan Islam
Dari tabel 2 di atas, dapat dijelaskan ada empat perbedaan pajak dalam Islam dan pajak dalam kapitalisme, yaitu :
Pertama, perbedaan dari segi dasar kewajiban pajak. Pajak dalam Kapitalisme, dasarnya bukanlah agama, melainkan teori-teori ekonomi tentang pajak, yaitu antara lain :
1.Teori Asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- Teori Kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- Teori Daya Pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
4.Teori Bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- Teori Asas Daya Beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. (https://wiki.v-tax.id/wiki/Teori-Teori_yang_mendukung_pemungutan_pajak).
Adapun pajak dalam Islam, didasarkan pada agama Islam itu sendiri, berupa dalil-dalil syariah dari al-Qur`an atau Al-Hadits, yang menjelaskan syarat-syarat seperti apa yang harus dipenuhi negara, supaya sah atau legal memungut pajak dari rakyat. Masalah ini diterangkan pada sub judul berikutnya, mengenai Kriteria-Kriteria Pajak Yang Dibolehkan Syariah.
Kedua, perbedaan dari segi apakah pajak itu sumber pendapatan negara yang tetap atau tidak tetap. Dalam Kapitalisme, pajak adalah sumber pendapatan yang tetap, dan bahkan lebih dari itu, pajak menjadi sumber utama dari pendapatan negara. Contohnya Indonesia, berdasarkan APBN 2025, lebih dari 82,1% pendapatan negara berasal dari perpajakan (pajak, bea, dan cukai), naik dari 77,5% di tahun sebelumnya. (https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh)
Ketiga, perbedaan dari segi kontinuitas (istimrāriyyah), yakni apakah pajak itu terus menerus dipungut dari rakyat, atau tidak terus menerus. Dalam Kapitalisme, pajak itu dipungut secara kontinu dari rakyat. Sedangkan pajak dalam Islam, tidak kontinu dipungut dari rakyat. Hal ini karena dalam APBN Syariah dalam negara Khilafah, pajak itu dipungut atau tidak, bergantung ketersediaan dana di Baitul Mal (Kas Negara). Jika ada dana di Baitul Mal, maka pajak tidak dipungut dari rakyat. Jika dana di Baitul Mal kurang atau bahkan tidak ada, maka barulah negara memungut pajak dari rakyat.
Keempat, perbedaan dari segi metode untuk mewajibkan pajak. Dalam Kapitalisme, pajak selalu ditetapkan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang, atau peraturan negara lainnya. Sedangkan dalam Islam, kewajiban pajak tidak selalu menggunakan metode penetapan undang-undang, tetapi dapat juga sekedar qarār (kebijakan) dari penguasa, disertai anjuran atau persuasi yang lebih menyentuh aspek ketakwaan dari individu-individu rakyat. (Syekh Mushthofa Mahmud Zaki, Al-Dharîbah fî Mîzân Al-Tasyrî’ Al-Islâmî, hlm. 12-15).
Kriteria-Kriteria Pajak Yang Dibolehkan Syariah
Pajak yang dibolehkan syariah, wajib memenuhi 4 (empat) kriteria (syarat) sebagai berikut :
Pertama, pajak dipungut untuk melaksanakan kewajiban syar’i yang menjadi kewajiban bersama antara kewajiban Negara (Baitul Mal) dan kewajiban kaum muslimin secara umum, misalnya kewajiban membantu kaum fakir dan miskin. Ini kewajiban negara, misalnya melalui zakat yang dikelola negara (QS Al-Taubah : 103), namun sekaligus juga kewajiban umat Islam (QS Al-Isra` : 26-27; QS Al-Baqarah : 177, dll). (Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hlm. 245; Muqaddimat Al-Dustur, Juz II, hlm. 117; Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulat Al-Khilafah, hlm. 122 & 130).
Kedua, pajak hanya dipungut temporal, tidak permanen, yakni ketika harta di Kas Negara kosong atau ada dananya tetapi tidak mencukupi kebutuhan. (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulat Al-Khilafah, hlm. 130).
Ketiga, pajak hanya dipungut dari kaum muslimin, tidak boleh dipungut dari warga non muslim.(Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hlm. 246).
Keempat, pajak hanya dipungut dari warga yang mampu, tidak boleh dipungut dari yang fakir atau miskin. (Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hlm. 246).
Inilah empat kiteria (atau syarat) yang wajib dipenuhi oleh penguasa (Khalifah) untuk memungut pajak. Jika keempat syarat itu semuanya terpenuhi, maka boleh hukumnya penguasa memungut pajak. Jika ada salah satu syarat atau lebih yang tidak terpenuhi, tidak boleh penguasa memungut pajak. Pemungutan pajak oleh penguasa yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, termasuk perbuatan zalim dan dosa besar yang akan mencegah penguasa masuk surga, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :
لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ
“Tidak akan masuk surga, siapa saja yang memungut cukai/pajak [yang tidak syar’i].” (HR Ahmad & Al-Hakim). (Taqiyuddin An-Nabhani, Muqaddimat Al-Dustur, Juz II, hlm. 117).
Apakah Pajak Saat Ini Sesuai Syariah?
Dengan memperhatikan 4 (empat) syarat untuk pajak syar’i di atas, jelaslah bahwa pajak yang dipraktikkan saat ini, bukanlah pajak yang sesuai syariah, melainkan pajak non syariah, yang hukumnya haram dipungut oleh negara saat ini dari rakyatnya.
Buktinya, pajak saat ini dipungut dari orang miskin, misalnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak pertambahan nilai (PPN), dsb, yang terbukti dari objek pajak secara umum, tidak peduli kaya atau miskin. Padahal seharusnya orang miskin itu bebas pajak (lihat syarat keempat pajak yang sesuai syariah).
Terlebih lagi, pajak yang dipraktikkan saat ini, jelas tidak memenuhi syarat pertama, yaitu pajak dipungut untuk melaksanakan kewajiban finansial bersama antara kewajiban negara dengan umat Islam. Artinya, peruntukan pajak itu wajib berupa sesuatu yang disyariatkan (masyrū’) yang hukumnya wajib, yang dibuktikan dengan dalil dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.
Adapun praktik pajak saat ini, peruntukannya ada yang dimaksudkan untuk sesuatu yang haram, misalnya membayar bunga utang. Pada tahun 2025 ini, bunga utang yang harus dibayar pemerintah diperkirakan mencapai Rp 552,1 triliun. (www.cnbcindonesia.com).
Apakah bunga dalam utang piutang sesuatu yang halal dalam Syariah Islam? Jelas haram, sesuai Fatwa MUI Pusat nomor 1 tahun 2004, yang memfatwakan bahwa bunga dalam utang piutang adalah riba yang hukumnya haram. Jadi, bagaimana mungkin, pajak yang peruntukannya untuk sesuatu yang haram, yaitu membayar riba, dikategorikan pajak yang sesuai syariah?
Kesimpulan dan Penutup
Pajak adalah adalah harta yang diambil dari warga negara untuk pengelolaan berbagai urusan negara. Inilah definisi pajak, yang secara umum maknanya sama antara pajak dalam Islam dan pajak dalam Kapitalisme.
Pajak itu ada dalam Islam, karena terbukti para ulama dari empat mazhab, telah membolehkan pemungutan pajak oleh Imam (Khalifah), walaupun istilah yang mereka pakai bukan al-dharibah, melainkan istilah-istilah lain yang sama maknanya dengan al-dharibah. Mereka menggunakan berbagai istilah untuk pajak yang kita pahami saat ini, misalnya istilah al-nawā`ib (النَّوَائِبُ), al-wazhā`if (الْوَظَائِفُ), al-tauzhif (التَّوْظِيفُ), dan al-kulafu al-sulthaniyyah (الْكُلَفُ السُّلْطَانِيَّةُ).
Meskipun ada kesamaan antara pajak dalam Islam dan pajak dalam Kapitalisme, akan tetapi ada sejumlah perbedaan yang kontras antara pajak dalam Islam dengan pajak saat ini yang berada di bawah sistem ekonomi kapitalisme.
Pajak boleh dipungut jika memenuhi semua syarat-syaratnya secara akumulatif. Terdapat empat syarat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani, rahimahullāh. Jika ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka haram bagi penguasa memungut pajak dari rakyatnya. Pajak saat ini terbukti tidak memenuhi empat syarat yang ada dalam Syariah Islam, dan wajib hukumnya dikoreksi agar sesuai dengan Syariah Islam. Wallāhu a’lam bi al-shawāb.
Yogyakarta, 23 Agustus 2025
Muhammad Shiddiq Al-Jawi