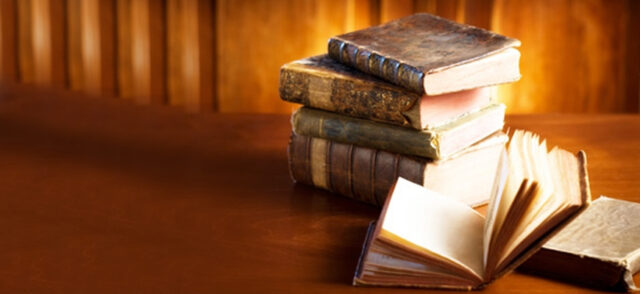
Tanya :
Ustadz, mohon dijelaskan contoh untuk kaidah tarjih hadits yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani di kitab Al-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah pada Juz I (hlm. 241), yang berbunyi sebagai berikut :
يُرَجَّحُ الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ عَلىَ خَبَرِ اْلآحَادِ
“Khabar (hadits) mutawātir lebih kuat daripada Hadist Āhād.” Mohon diberikan contohnya. (Faiz, Klaten).
Jawab :
Memang dalam kitab karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani tersebut, tidak disebutkan contoh aplikasi dari kaidah tarjih yang ada. Hal ini sebenarnya bukanlah suatu aib, karena beliau mengikuti metode mutakallimin dalam persoalan perumusan kaidah ushuliyah, yaitu merumuskan kaidah ushuliyah terlebih dulu secara murni, tanpa melihat apakah furū’-nya, yaitu contoh dan aplikasinya, ada atau tidak. Metode mutakallimin ini merupakan metode jumhur ulama, yaitu metode para ulama Malikiyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah. (Muhammad Husain Abdullah, Al-Wāḍih fī Uṣūl al-Fiqh, hlm. 32).
Metode tersebut berbeda dengan metode fuqoha`, yaitu metode ulama Hanafiyah yang merumuskan kaidah ushuliyah berdasarkan furū’-nya, yakni contoh-contoh kasusnya, yang sudah ada terlebih dahulu. Sebuah kaidah ushuliyah yang dirumuskan berdasarkan metode fuqoha`, sudah barang tentu akan banyak contoh dan aplikasinya. (Muhammad Husain Abdullah, Al-Wāḍih fī Uṣūl al-Fiqh, hlm. 33).
Namun terlepas dari metodenya, memang benar bahwa ketiadaan contoh dari suatu kaidah, akan dapat menimbulkan kesulitan tersendiri, khususnya bagi mereka yang mungkin tidak sabar membaca kitab-kitab ushul fiqih karya para ulama yang jumlahnya sangat banyak yang mungkin melelahkan dan menjemukan bagi orang yang tidak terbiasa menekuni disiplin ilmu yang pelik dan kompleks seperti ilmu ushul fiqih ini. Kesulitan tersebut muncul karena kaidah tarjih yang ada hanyalah menjadi informasi (ma’lūmāt) bagi mereka itu, tetapi belum menjadi persepsi (mafāhīm) yang sempurna dalam benak mereka mengenai kaidah tarjih tersebut, karena kaidah tersebut belum dipertemukan dengan fakta (al-wāqi’) yang dimaksudkan, yaitu contoh aplikasinya. (Taqiyuddin An-Nabhani, al-Shakhshiyyah al-Islāmiyyah, 1/12; Al-Tafkīr, hlm.20-21).
Maka dari itu, kami sajikan 2 (dua) contoh berikut ini, sejauh yang dapat kami peroleh dari kitab-kitab ushul fiqih para ulama. Mudah-mudahan dengan contoh yang ada kita lebih memahami kaidah tarjih tersebut.
Contoh pertama, terdapat kontradiksi (al-ta’āruḍ) antara dua hadits berikut ini :
Pertama, hadits dari Ibnu ‘Umar RA berikut ini :
عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ… رواه البخاري (735).
Dari Ibnu ‘Umar RA, bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya ketika memulai shalat, dan ketika takbir untuk rukuk, dan ketika bangkit dari rukuk… (HR Bukhari, no. 735).
Kedua, hadits dari Abdullah bin Mas’ud RA sebagai berikut :
عن عبدالله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قال : أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. رواه الترمذي (257)، وحسنه، وصحَّحه الألباني
Dari Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkata,”Maukah kamu bila aku shalat bersama kamu dengan cara shalatnya Rasulullah SAW?” Lalu Ibnu Mas’ud RA pun melaksanakan shalat dan dia tidak mengangkat kedua tangannya, kecuali takbir pada saat yang pertama kali (saat takbiratul ihram).” (HR Tirmidzi, no. 257, dan Imam Tirmidzi menilainya sebagai hadits hasan. Syekh Nashiruddin Al-Albani menilai hadits ini hadits shahih).
Hadits pertama bertentangan dengan hadits kedua, karena hadits pertama menetapkan bahwa Rasulullah SAW bertakbir pada saat takbiratul ihram, pada saat ruku’, dan pada saat bangkit dari ruku’. Sedangkan hadits kedua, menetapkan bahwa Rasulullah SAW bertakbir pada saat takbiratul ihram saja, tidak ada yang lain.
Tarjihnya, hadits pertama lebih kuat (rājih) daripada hadits yang kedua, karena hadits pertama adalah hadits mutawatir, sedangkan hadits yang kedua adalah hadits Ahad.
Berkata Imam Ibnu Rusy Al-Jadd dalam kitab Al-Bayān wa al-Taḥṣīl (1/261) :
وَالصَّحِيحُ فِي المَذْهَبِ إِيجَابُ الرَّفْعِ فِي ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ ، فَهُوَ تَوَاتَرَتْ بِهِ الْآثَارُوَأَخَذَ بِهِ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ
“Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab (Maliki), wajib hukumnya mengangkat tangan pada yang demikian itu berdasarkan As-Sunnah, cara takbir ini telah diriwayatkan secara mutawatir dalam berbagai hadits, dan telah diambil oleh sekumpulan para fuqoha’ di berbagai kota.” (Ibnu Rusy Al-Jadd, Al-Bayān wa al-Taḥṣīl, 1/261).
Bertakbir di tiga tempat tersebut (saat takbiratul ihram, saat ruku’, dan saat bangkit dari ruku’) juga merupakan pendapat dalam mazhab Syafi’i. Imam Syafi’i berkata dalam kitabnya Ikhtilāf al-Hadīth :
بِهَذِهِ اْلأَحَادِيْثِ – أَيْ أَحَادِيْثُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ – تَرَكْنَا مَا خَالَفَهَا مِنْ حَدِيْثٍ، لِأَنَّهَا أَثْبَتُ إِسْنَادًا، وَأَنَّهُ حَدِيْثُ عَدَدٍ، وِالْعَدَدُ أَوْلىَ بِالْحِفْظِ
“Dengan hadits-hadits ini –yaitu hadits-hadits tentang mengangkat tangan – kami meninggalkan hadits yang menyalahi hadits-hadits tentang mengangkat tangan, karena hadits-hadits itu lebih kokoh isnad-nya, dan hadits-hadits itu merupakan hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang (hadits mutawatir), padahal hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang (hadits mutawatir), lebih layak untuk dipelihara.” (Imam Syafi’i, Ikhtilāf al-Hadīth, hlm. 127).
(Sumber : https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/793/1/2/166080).
Contoh kedua, terdapat kontradiksi (al-ta’āruḍ) antara dua hadits berikut ini :
Pertama, hadits dari ‘Abdullah Ibnu ‘Abbas RA berikut ini :
عَنْ عبدالله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ. رواه الترمذي (5/ 221)، وابن حبان في صحيحه (5440)، وصححه الألباني
Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,”Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,’Jika kulit binatang telah disamak, maka ia menjadi suci.” (HR Tirmidzi, 5/221; Ibnu Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban (nomor 5440), dan hadits ini dinilai shahih oleh Syeikh Nashiruddin Al-Albani).
Kedua, hadits dari ‘Abdullah bin’Ukaim RA berikut ini :
وعَنْ عبدالله بن عُكَيْمٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ) . رواه البزار، مسند البزار (13/ 50)، وشرح مشكل الآثار، للطحاوي (12/ 509)، والكفاية، للخطيب البغدادي، صـ (168).
Dari ‘Abdullah bin’Ukaim RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Janganlah kamu memanfaatkan dari bangkai maupun urat bangkai, dengan melakukan penyamakan.” (HR Al-Bazzār, Musnad Al-Bazzār, 13/50; Al-Thahāwi, Sharah Mushkil al-Āthār; Al-Khaṭīb al-Baghdādi, Al-Kifāyah fī ‘Ilmi al-Riwāyah, hlm. 168).
Hadits pertama bertentangan dengan hadits kedua, karena hadits pertama menetapkan bahwa kulit bangkai menjadi suci dengan cara menyamaknya. Sedangkan hadits kedua, menetapkan kulit bangkai tidak menjadi suci, baik dengan cara menyamaknya maupun dengan cara yang lainnya.
Tarjihnya, hadits pertama lebih kuat (rājih) daripada hadits yang kedua, karena hadits pertama adalah hadits mutawatir, sedangkan hadits yang kedua adalah hadits Ahad.
Imam Al-Thahāwi menegaskan bahwa hadits pertama dari Ibnu Abbas RA di atas adalah hadits mutawatir dengan berkata :
قال الإمام الطحاوي: (فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ، وهي ظاهرة المعنى…) شرح معاني الآثار، للطحاوي 1/ 471
Imam al-Thahāwi berkata,”Sungguh telah terdapat hadits-hadits yang datang secara mutawatir mengenai sucinya bangkai dengan penyamakan, dan ini sangat jelas maknanya. Hadits ini lebih utama daripada hadits Abdullah bin ‘Ukaim …” (Al-Thahāwi, Sharah Mushkil al-Āthār, 1/471).
(Sumber : https://www.alukah.net/sharia/0/145067/المرجحات-عند-التعارض-ثلاثة-وعشرون-مرجحا-1ixzz7qNGIujQy).
Hanya saja, perlu kami tambahkan bahwa memang sebagian ulama telah meletakkan kedua hadits di atas bukan dalam konteks tarjih hadits, melainkan dalam konteks nasakh (penghapusan hukum) hadits. Sebagian ulama itu berpendapat, bahwa hadits kedua yang melarang penyamakan kulit bangkai secara mutlak, merupakan hadits yang secara kronologi waktunya lebih belakangan (muta`akhkhir) daripada hadits pertama. Maka dari itu, hadits kedua ini dianggap menasakh hadits pertama yang membolehkan menyamak kulit bangkai binatang.
(Sumber : https://www.dorar.net/hadith/sharh/28519).
Hanya saja, pendapat tersebut tidak dapat diterima, karena hadits pertama adalah hadits mutawatir, sedang hadits kedua adalah hadits Ahad, padahal terdapat kaidah ushuliyah yang sudah menetapkan bahwa Hadits Mutawatir tidak dapat dinasakh oleh hadits Ahad. Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam masalah ini menyatakan :
أَمَّا الْمُتَوَاتِرُفَلاَ يَجُوْزُ أَنْ يُنْسَخَ إِلاَّ بِالْمُتَوَاتِرِ، فَلاَ يُنْسَخُ الْمُتَوَاتِرُ بِاْلآحَادِ
“Adapun Hadits Mutawatir, maka dia tidak boleh dinasakh kecuali oleh Hadits Mutawatir pula, maka tidak boleh terjadi nasakh Hadits Mutawatir oleh Hadits Ahad.” (Taqiyuddin An-Nabhani, Al-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah, 3/282).
Demikianlah penjelasan kami, semoga bermanfaat. Āmīn. Wallāhu a’lam.
Yogyakarta, 25 Januari 2023
Muhammad Shiddiq Al-Jawi





































