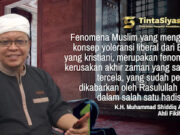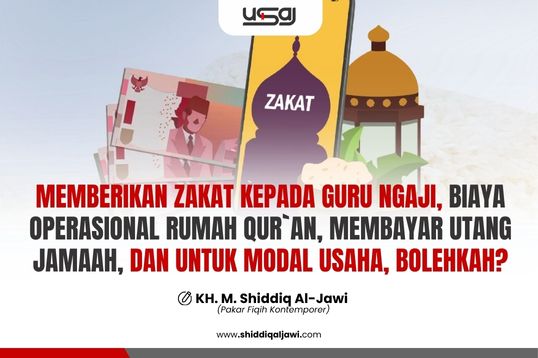
Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi | Pakar Fiqih Kontemporer
Tanya :
Ustadz, afwan untuk dana penerimaan zakat maal, apakah boleh dialokasikan ke :
- kafalah guru ngaji (asatidz) di Rumah Quran gratis.
- biaya operasional Rumah Quran (makan asatidz, listrik, iuran sampah, iuran RT dll).
- pembayaran hutang jamaah yang terlilit hutang.
- modal usaha jamaah yang diputar secara bergilir. (Hesti Nugrahani, Jakarta).
Jawab :
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, akan dijelaskan secara tertib (urut) 3 (tiga) hal sebagai berikut;
Pertama, 8 (delapan) golongan yang berhak mendapat zakat,
Kedua, pengertian fī sabīlillāh pada ayat zakat (QS. At-Taubah : 60),
Ketiga, baru akan dijawab empat pertanyaan tersebut satu per satu.
Delapan Golongan Yang Berhak Menerima Zakat
Para penerima zakat ini disebut dengan istilah mashārif al-zakāt (مَصَارِفُ الزَّكَاةِ) atau delapan ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat sesuai QS At-Taubah : 60. Firman Allah SWT :
اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ
“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah milik orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS At-Taubah : 60).
Penjelasan untuk masing-masing golongan tersebut adalah sebagai berikut;
Pertama, Al-Fuqarā’, bentuk jamak (plural) dari al-faqīr, yang berarti orang yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan).
Kedua, Al-Masākīn, bentuk jamak (plural) dari al-miskīn, yang artinya orang yang tidak mempunyai apa-apa.
Ketiga, ‘Āmil Zakāt, yaitu orang-orang yang diangkat Imam/Khalifah untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat dan membagikan kepada para penerima zakat (mashārif al-zakāt).
Keempat, Mu’allaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam yang menurut Imam/Khalifah layak mendapat zakat untuk memperkokoh iman mereka.
Kelima, Hamba sahaya (budak). Jika mereka budak mukātab, yakni ada perjanjian kemerdekaan dirinya dari tuannya jika budaknya mempunyai uang tertentu untuk menebus dirinya, dia dibeli dengan uang zakat. Jika bukan budak mukātab, dimerdekakan dengan uang zakat.
Keenam, Al-Ghārimīn, bentuk jamak (plural) dari al-ghārim, yang artinya orangorang yang mempunyai utang karena 3 (tiga) sebab, sebagai berikut;
Pertama, li ishlāhi dzātil bain, yaitu berutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa.
Kedua, li daf’i al-diyyat, yaitu berutang untuk membayar diyat (tebusan) dalam kasus pidana pembunuhan.
Ketiga, li qadhā`i al-mashālih al-khāshshah, yaitu berutang untuk memenuhi keperluan-keperluan khusus, misal untuk berbisnis, berobat, menikah, dsb.
Ketujuh, Fī Sabīlillāh (untuk berperang jihad fī sabīlillāh). Yaitu untuk orang-orang yang berjihad (berperang) di jalan Allah, atau untuk segala keperluan yang secara langsung terkait jihad, seperti pendidikan militer, latihan militer, dan industri senjata.
Kedelapan, Ibnu Sabīl. Yaitu orang-orang yang terputus dari safarnya (al-munqathi’ fī safarihi), dalam arti tidak punya harta lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Maka dia diberi zakat agar dapat melanjutkan perjalanan hingga ke kampung halamannya. (‘Abdul Qadim Zallum, Al–Amwāl fī Daulah Al–Khilāfah, hlm. 173-177; Taqiyuddin An-Nabhani, Al-Nizhām Al-Iqtishādī fī Al-Islām, hlm. 241; Muqaddimat Al-Dustūr, Juz II, hlm. 105).
Pengertian Fī Sabīlillāh Pada Ayat Zakat (Qs At-Taubah : 60)
Ada khilāfiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama mengenai penafsiran istilah fī sabīlillāh pada ayat tentang delapan ashnaf (golongan) mustahiq zakat (QS At-Taubah : 60).
Pendapat pertama, jumhur (mayoritas) ulama menafsirkan kata fī sabilīllāh dalam QS At-Taubah itu secara khusus, yaitu jihad fī sabīlillāh dalam arti perang (qitāl) dan segala sesuatu yang terkait perang, misalnya membeli senjata dan alat perang.
(Imam Al-Thabarī, Tafsīr Al-Thabarī, 14/319; Imam Al-Qurthubi (Tafsīr Al-Qurthubī), 8/185; Imam Ibnu Arabi, Ahkāmul Qur`ān, 4/337; Imam Al-Jashash, Ahkāmul Qur`ān, 7/70); dan Imam Syafi’ī, Ahkāmul Qur`ān, 1/123).
Imam Jalaluddin As-Suyuthi, misalnya, menafsirkan fī sabilīllāh dalam QS At-Taubah : 60 itu dengan berkata :
هُمُ الْمُجَاهِدُوْنَ
“Mereka (fī sabilīllah) adalah para mujahid (humul mujāhidūn) (orang yang berjihad/berperang di jalan Allah).” (Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Ad-Durr Al-Mantsūr, 5/101; Al-Iklīl fī Istinbāth Al-Tanzīl, hlm. 120).
Pendapat kedua, pendapat sebagian ulama yang menafsirkan fī sabilīllāh secara umum, yaitu segala jalan kebajikan (fī jamī’i wujūh al-khair).
Imam Fakhrur Razi, misalnya, menafsirkan fī sabilīllāh dalam arti segala jalan kebajikan, misal mengkafani mayat, membangun benteng, dan memakmurkan masjid (‘imāratul masājid).
(Imam Fakhrur Razi, Mafātihul Ghaib, 8/76; Imam Al-Khazin, Lubāb At-Ta`wīl fī Ma’ānī At-Tanzīl, 3/295; Imam Jamaluddin Al-Qasimi, Mahāsin At-Ta`wīl, 8/3181; Imam Al-Alusi, Rūhul Ma’ānī, 7/271; Sayyid Rasyid Ridho, Al-Manār, 10/587; Sayyid Quthub, Fī Zhilāl Al-Qur`ān, 4/34; dan Syaikh Al-Maraghi, Tafsīr Al-Marāghī, 10/145).
Pendapat yang rājih (lebih kuat), adalah pendapat jumhur ulama, bahwa fī sabīlillāh itu artinya adalah jihad, yaitu perang (qitāl) dan segala sesuatu yang terkait perang secara langsung. Terdapat 2 (dua) alasan pentarjihan sebagai berikut;
Pertama, karena kata “fī sabilīllāh” yang terdapat dalam Al-Qur`an, jika dihubungkan dengan kata “infaq” (pembelanjaan harta), pada dasarnya mempunyai arti khusus, yaitu jihad fī sabilīllāh. Kecuali jika terdapat qarīnah (indikasi) yang memindahkan maknanya dari makna jihad ke makna kebaikan secara umum, maka “fī sabilīllāh” berarti kebaikan secara umum (misalnya QS 2:261).
(Taqiyuddin An-Nabhani, Al-Nizhām Al-Iqtishādī fī Al-Islām, hlm. 234; Abdul Qadim Zallum, Al-Amwāl fī Daulat Al-Khilāfah, hlm. 173-174).
Kedua, jika kata fī sabilīllāh diartikan secara umum, yaitu untuk semua jalan kebajikan (fī jamī’i wujūh al-khair), maka ayat itu (QS At-Taubah : 60) maknanya justru menjadi kabur dan tidak jelas. Sebab semua jalan kebajikan artinya luas dan umum, termasuk di dalamnya memberi harta zakat kepada tujuh ashnaf lainnya, yakni orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, ibnu sabil, dan orang berhutang (ghārimīn).
Memberi harta kepada orang fakir, adalah suatu jalan kebajikan, berarti merupakan fī sabilīllah. Memberikan harta kepada orang miskin, adalah juga suatu jalan kebajikan, berarti juga merupakan fī sabilīllah. Memberikan harta kepada amil zakat, ibnu sabil, dan ghārimīn, juga merupakan jalan-jalan kebajikan, dan berarti itu semua termasuk pula ke dalam fī sabilīllāh.
Lalu apa bedanya memberikan zakat kepada ke tujuh ashnaf itu, dengan memberi zakat kepada fī sabilīllāh? Bukankah jika fī sabilīllāh diartikan secara umum meliputi semua jalan kebaikan, maka makna dari ayat QS At-Taubah : 60 itu menjadi kabur dan tidak jelas?
Jadi, artinya, kata fī sabilīllāh pada ayat itu haruslah memiliki makna khusus (bukan makna umum), yaitu jihad, agar dapat dibedakan secara jelas maknanya dengan tujuh ashnaf lainnya sebagai penerima zakat. Jadi, makna fī sabilīllāh yang tepat adalah jihad, bukan yang lain.
===============
Memberikan Zakat Kepada Guru Ngaji
Tanya :
Bolehkah memberikan zakat kepada guru ngaji (asatidz)?
Jawab :
Tidak boleh, karena guru ngaji (asatidz) tidak termasuk ke dalam salah satu dari delapan ashnaf (golongan) yang berhak mendapat zakat, sebagaimana dalam QS At-Taubah : 60.
Guru ngaji (asatidz) juga tidak termasuk golongan fī sabilīllāh, karena pengertian yang benar dari fī sabilīllāh itu bukan “semua jalan kebaikan” melainkan dalam jihad (berperang) fi sabilillah.
Kecuali, jika guru ngaji (asatidz) itu orang fakir atau miskin, maka dia diberi zakat karena termasuk fakir atau miskin, bukan karena dia guru ngaji.
===============
Memberikan Zakat Untuk Biaya Operasional Suatu Kegiatan
Tanya :
Bolehkah memberikan zakat untuk operasional kegiatan, misalnya untuk makan asatidz, listrik, iuran sampah, iuran RT dll?
Jawab :
Tidak boleh, karena kegiatan-kegiatan tersebut walaupun kegiatan yang Islami, tetapi tidak termasuk fī sabilīllāh, karena pengertian yang benar dari fī sabilīllāh itu bukan “semua jalan kebaikan” melainkan berjihad (dalam arti berperang) fī sabilīllāh.
Untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan Islami seperti itu, gunakanlah dana yang diperoleh melalui sedekah atau infaq yang sifatnya umum, bukan dibiayai dari dana zakat karena zakat itu sudah ada ketentuannya secara khusus mengenai siapa saja yang berhak menerimanya.
===============
Memberikan Zakat Untuk Membayar Utang Jamaah
Tanya :
Bolehkah memberikan zakat untuk pembayaran hutang jamaah yang terlilit hutang?
Jawab :
Boleh, namun individu penerima zakat harus memenuhi 3 (tiga) syarat sbb :
Pertama, pastikan bahwa penerima zakat itu muslim (bukan non-muslim) karena non muslim tidak berhak mendapat zakat. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Dalil untuk syarat pertama ini, sabda Nabi SAW :
أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِ
“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka (kaum muslimin) zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka (kaum muslimin) dan dibagikan kepada orang-orang fakir mereka (kaum muslimin).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Kedua, pastikan utang yang dia ambil itu untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syariah, bukan untuk tujuan yang diharamkan syariah.
Ketiga, jika utangnya adalah utang ribawi, pastikan zakat yang diberikan hanya untuk membayar pokok utangnya, karena tidak boleh zakat digunakan untuk membayar bunga utang (riba).
Dalil untuk syarat kedua dan ketiga, bahwa Allah SWT telah melarang memberi bantuan untuk melakukan perbuatan dosa atau perbuatan haram. Firman Allah SWT :
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ
“Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Ma`idah : 2).
==================
Memberikan Zakat Untuk Modal Usaha Secara Bergilir
Tanya :
Bolehkah memberikan zakat untuk modal usaha secara bergilir?
Jawab :
Tidak boleh, dengan 3 alasan sbb :
Pertama, karena tidak ada dalil Al-Qur`an dan Al-Hadits yang menunjukkan bolehnya memberikan zakat untuk modal usaha. Perlu diketahui zakat itu adalah ibadah murni (ibadah mahdhah) yang ketentuannya bersifat tauqīfī (apa adanya) dari Allah SWT. Maka sesuatu yang tidak ada dalilnya, berarti tidak disyariatkan atau tidak diperbolehkan.
Imam Taqiyuddin An-Nabhani berkata :
أَحْكَامُ الْعِبَادَاتِ تَوْقِيفِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
Ahkāmul ‘ibādāti tauqīfiyyatun min ‘indillāh. Artinya,“Hukum-hukum ibadah itu sifatnya tauqifiyyah dari sisi Allah.” (Muhammad Muhammad Isma’il/Taqiyuddin An-Nabhani, Al-Fikr Al-Islāmī, hlm. 48).
Yang dimaksud hukum ibadah itu tauqifiyyah (تَوْقِيفِيَّةٌ) adalah :
أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعَبُّدُ لِلَّهِ تَعَالَى بِعِبَادَةٍ إِلَّا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِبَادَةُ قَدْ ثَبَتَ فِي النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (اَلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) أَنَّهَا عِبَادَةٌ شَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى.
“Bahwa tidak boleh beribadah kepada Allah SWT dengan suatu ibadah, kecuali jika ibadah ini telah terbukti di dalam nash-nash syariah (ada dalilnya dari Al-Qur`an dan As-Sunnah), yakni bahwa ibadah itu telah disyariatkan oleh Allah SWT.” (https://islamqa.info/ar/answers/147608).
Jadi karena tidak ada dalilnya, maka memberikan zakat untuk modal usaha secara bergilir tidak diperbolehkan dan statusnya adalah batil. Kaidah fiqih menegaskan :
الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ
Al-Ashlu fil ‘ibādāti al-buthlānu hattā yaquma dalīlun ‘alā al-amri. Artinya,“Hukum asal ibadah itu adalah batil, hingga terdapat dalil yang memerintahkan (ada dalilnya dari Al-Qur`an atau As-Sunnah).” (Abu ‘Abdirrahman Abdul Majid Jumu’ah Al-Jaza`iri, Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah Al-Mustakhrajah min Kitāb I’lāmul Muwaqqi’īn, hlm. 539).
Dalam redaksi yang lain yang semakna, terdapat kaidah fiqih yang berbunyi :
الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْإِذْنِ بِهِ
Al-Ashlu fil ‘ibādāti al-man’u hattā yaquma dalīlun ‘alā al-idzni bihi. Artinya,”Hukum asal ibadah itu adalah tidak boleh hingga terdapat dalil yang mengizinkan ibadah itu.” (Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Manzhūmah Ushūl Al-Fiqh wa Qawā’iduhu, hlm. 95).
Kedua, karena pemberian zakat sebagai modal usaha yang dilakukan secara bergilir itu, tidak termasuk ke dalam 8 golongan penerima zakat (Lihat QS. At-Taubah : 60). Sebuah kaidah fiqih tentang zakat menyebutkan :
إِنَّ الزَّكَاةَ لَا يُصْرَفُ لِغَيْرِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ مُطْلَقًا
Inna az-zakāta lā yushrafu li-ghairi al-ashnāf al-tsamāniyyah. Artinya, “Sesungguhnya zakat itu tidak boleh disalurkan kepada orang-orang di luar delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat secara mutlak.” (Taqiyuddin An-Nabhani, Muqaddimat Al-Dustūr, Juz II, hlm. 105).
Ketiga, karena jika zakat diserahkan untuk modal usaha, artinya pemberian zakat kepada 8 golongan akan tertunda atau bahkan terabaikan sama sekali tanpa alasan yang dibenarkan syariah, padahal pembagian zakat kepada 8 golongan itu wajib hukumnya karena mereka inilah pemilik yang sebenarnya dari harta zakat. Maka pemberian zakat untuk modal usaha tidak diperbolehkan.
Dengan kata lain, pembagian zakat kepada kaum fakir dan miskin, wajib dilakukan dengan segera (‘ala al-faur), tanpa penundaan (‘ala al-tarākhī), karena penundaan dapat mengibatkan dharar (mudharat) bagi orang fakir dan miskin itu, misalnya kelaparan, kurang gizi, dsb. Kaidah ushul fiqih untuk kasus seperti ini yang mengharuskan kesegeraan, menyebutkan :
الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ
Al-Amru yaqtadhī al-faur. Artinya, “Suatu perintah itu mengharuskan dilakukan secara segera (tidak boleh ada penundaan).” (‘Abdul Karim Al-Namlah, Ittihāfu Dzawil Bashā`ir bi Syarh Raudhat Al-Nāzhir, Juz V, hlm. 303; Imam Al-Zarkasyi, Al-Bahrul Muhīth fī Ushūl Al-Fiqh, Juz II, hlm. 134).
Kesimpulannya, tidak boleh secara syariah memberikan zakat untuk modal usaha secara bergilir, berdasarkan 3 (tiga) alasan di atas. Wallāhu a’lam.
Yogyakarta, 24 Oktober 2025
Muhammad Shiddiq Al-Jawi